Dari monster purba hingga makhluk ekstra-terestrial, sebagai seorang sutradara, Steven Spielberg sudah menyelami semuanya. Namanya pun lebih besar dari waralaba film apa pun, walaupun ketenarannya menurun sejak dekade 2010 ini. Namun, pada fase ini, ia taklekang oleh waktu dan karyanya makin menarik.
Dalam kariernya yang gemilang dan penuh warna-warni, apalagi yang dapat diselami oleh Spielberg? Jawabannya ternyata ada dalam dirinya sendiri: menyelami masa lalunya. Ia pun membentuk The Fabelmans, kisah semi otobiografi yang ditulis bersama Tony Kushner yang telah bekerja sama dengannya dalam film Munich (2005), Lincoln (2012), dan yang teranyar, West Side Story (2021).
Menceritakan diri sendiri dalam sebuah film dapat menghasilkan kisah yang sangat egosentris dan naif. Spielberg sendiri belum pernah menulis skenario orisinil yang ia sutradarai sendiri sejak Close Encounters of the Third Kind (1977). Hadirnya Kushner dalam Fabelmans pun memberikan dimensi lebih dalam kisah masa kecil sang sineas ini.
Spielberg menyamarkan dirinya dalam sosok Sam Fabelmans (Gabriel LaBelle) lelaki muda keturunan Yahudi yang dirangsang untuk menyukai sinema oleh ibunya, Mitzi (Michelle Williams). Ia pun menekuni hobinya sebagai sineas, yang keseriusannya dipertanyakan oleh ayahnya, Burt (Paul Dano), yang konvensional. Terlepas dari kisah Sam dengan segala rintangan gapai cita-citanya sebagai sineas, dimensi film ini merayap ke kehidupan keluarga dan pernikahan.
Kisah Sam mungkin satu hal yang menarik untuk disaksikan. Walaupun mengisahkan dirinya sendiri, takhadir kesan pemaksaan idealisme atau penyombongan diri terhadap Spielberg. Jika ada sedikit pujian terhadap Sam, memang layak diberikan kepada karakternya dan kita takkan terbesut bahwa itu cara Spielberg membesarkan egonya.
Kisah intim terhadap perkembangan Sam, terlahirnya seorang sineas, dan lingkungan sekitarnya, memang jadi fokus menarik. Spielberg memang seperti menulis surat cinta terhadap dirinya sendiri, tetapi kisah multidimensionalnya pun bisa menjadi surat cinta terhadap para sineas, baik itu yang telah berjuang melewati fase awalnya maupun yang sedang berada dalam fase tersebut. Terlebih lagi, ia pun menyisipkan porsi besar untuk mengucapkan rasa sayangnya terhadap kedua orang tuanya.
Menjadi sosok ayah yang tenang dan sabar mungkin lembaran baru dari karier Dano yang penuh corak. Sosoknya pun melebur di dalam Fabelmans mengikuti arus yang dibawa oleh Sam dan Mitzi. Nama terakhir ini yang jadi sorotan dan benar-benar mencuri perhatian film ini dari karakter utama.
Mitzi benar-benar memberikan corak yang berbeda dalam kisah Fabelmans. Kisahnya sebagai perempuan berbakat artistik besar yang terkekang realitas sebagai istri konvensional menciptakan kompleksitas hebat dalam karakternya. Dalam karier hebatnya sebagai sutradara berdekade-dekade, Mitzi yang ditulis berdasarkan sosok ibunya, alm. Leah Adler, mungkin karakter terhebat yang pernah hadir dalam film Spielberg.
Williams pun memerankannya dengan brilian, salah satu performa terbaik tahun ini. Segala cakrawala emosi dikuasainya dalam karakter ini. Sosoknya energik, tetapi ia paham benar kapan energi tersebut membara dan kapan energi tersebut padam. Pergerakannya pun begitu indah, terutama dalam salah satu adegan hebat saat berkemah: tarian gemulai ajaibnya menyentuh hati. Kehadiran karakter ini pun menjadi surat cinta terindah Steven kepada Leah.
Dengan segala kompleksitas menjadi sineas, kesulitan sosial Sam sebagai keturunan Yahudi, maupun terungkapnya sisi lain ibunya, Spielberg takmenjadikan filmnya dalam dimensi-dimensi gelap saja. Ia mengembalikan esensi Fabelmans sebagai film keluarga yang bisa dinikmati oleh segala kalangan. Banyak kemenangan-kemenangan kecil yang diraih Sam yang membuat kita girang. Candaan-candaan dan suasananya pun dibuat riang, hidup layaknya keluarga muda dengan teriakan-teriakan anak-anak Fabelmans.
Konflik-konflik terberat film ini pun diperhalus. Spielberg mencurahkan emosi-emosi masa mudanya, tetapi ia memandangnya dari dirinya yang sudah dewasa. Saat satu karakter melakukan kesalahan, diberi juga berbagai macam prespektif untuk memahami kisahnya. Sisi ini mungkin dipoles terlalu halus oleh Spielberg. Begitu pula dengan visual-visual dalam filmnya ini, walau terlihat cantik, tetapi terlihat takorganik.
Bagi Spielberg yang film-filmnya selalu merakyat, Fabelmans mungkin karyanya yang penikmatnya paling spesifik. Saya pun teringat dengan pertanyaan teman, “memang ada yang mau menyaksikan film otobiografi seorang sineas?” Saya pun harus mempereteli siapa itu Spielberg dan seberapa besar sosoknya dalam dunia perfilman.
Pertanyaan itu menduri, tetapi menciptakan karya seni seharusnya takterlalu memusingkan siapa peminatnya. Hal terpenting ialah pesan yang ingin disampaikan dan Spielberg menyampaikannya dengan cara yang paling manis dalam film ini. Kita sedang memasuki fase akhir dari salah satu sineas terkondang dan terbesar pada abad ke-20 dan ke-21. Lalu, dalam fase akhir ini, ia masih terus menciptakan karya-karya hebat. Menyimak Fabelmans pun cukup duduk manis selama dua setengah jam, lalu menikmati hidangan sedap dari Spielberg.
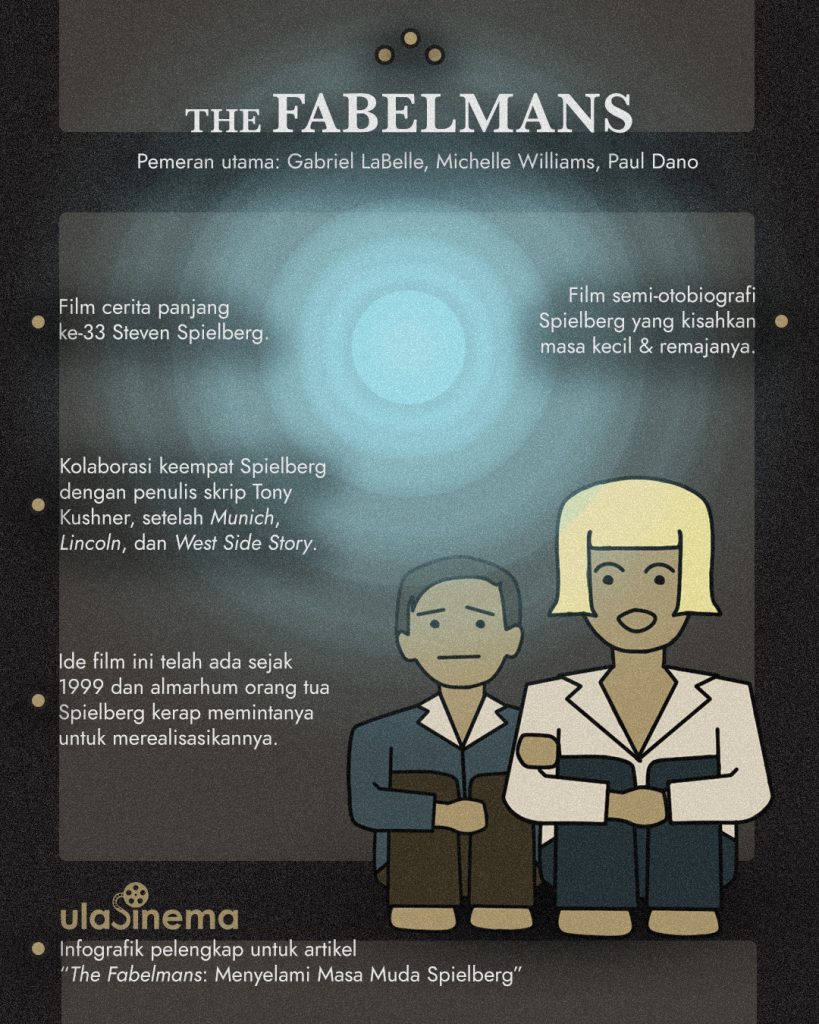
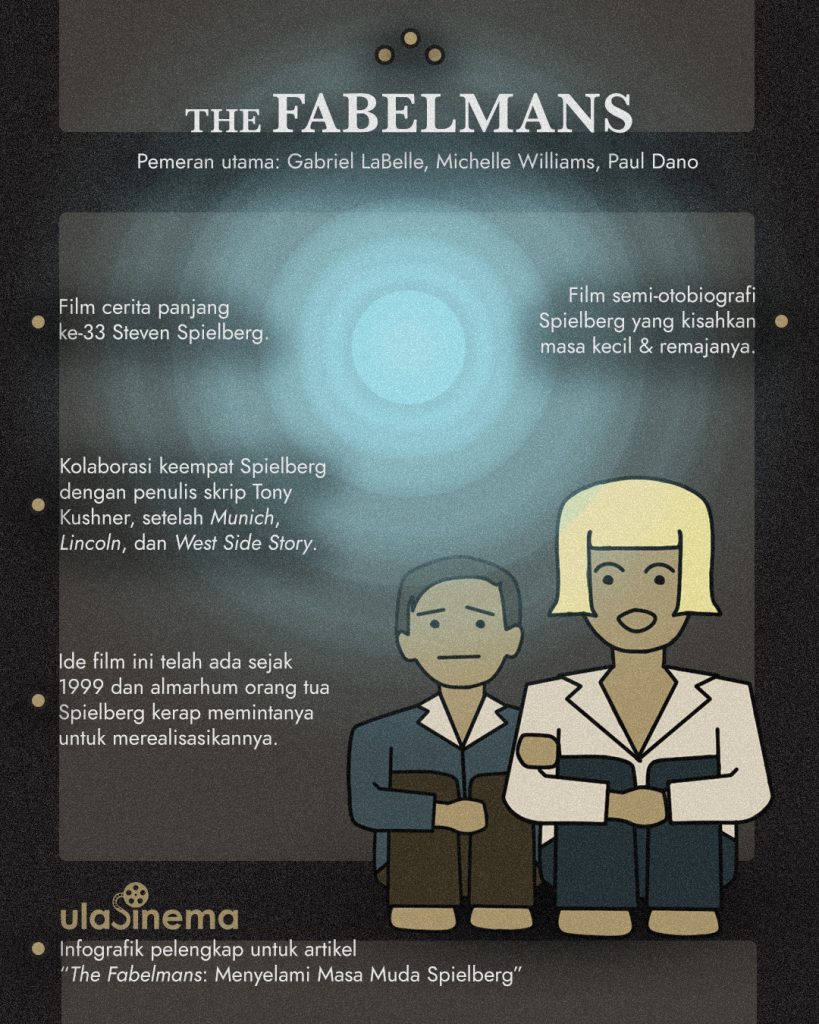
Baca juga: Review The Unbearable Weight of Massive Talent (2022)
Penulis: Muhammad Reza Fadillah




















